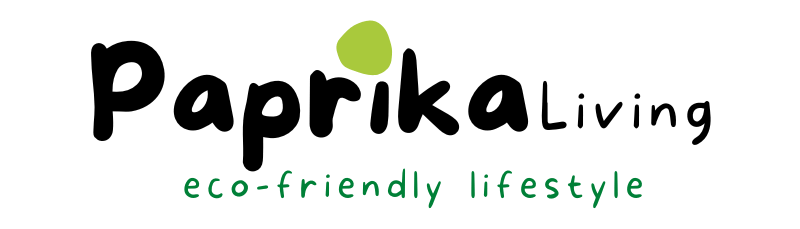Oleh Mariska Pricilla
Krisis pangan di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim kini banyak didiskusikan. Hal ini tambah mengkhawatirkan mengingat prediksi populasi dunia yang semakin berkembang. United Nations (2019) memperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 9,7 miliar orang di tahun 2050, karenanya produksi pangan harus meningkat sebanyak 70% untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dunia.
Ironisnya, perubahan iklim salah satunya juga disebabkan oleh proses produksi pangan sendiri. Misalnya saja, emisi karbon yang dihasilkan dari peternakan sapi, berdampak pada ketidakstabilan dalam produksi pangan dan menurunkan produktivitas produksi pangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya perubahan fundamental dalam produksi pangan.
Mungkin kamu pernah mendengar seruan untuk mengurangi produk susu dalam kampanye perubahan iklim. Apa hubungannya? Konsumsi pangan hasil ternak seperti susu sapi dan daging sapi memiliki dampak signifikan pada perubahan iklim dikarenakan penggunaan air dan lahan yang besar serta pembuangan emisi karbon.
Sapi merupakan hewan ternak dengan emisi karbon terbesar, diikuti oleh babi, ayam, lalu kerbau. Menurut FAO, emisi yang dihasilkan dari peternakan sapi menyumbang 62% dari total gas rumah kaca yang dihasilkan sektor peternakan di dunia, 30% dari produk susu dan 32% dari produk daging.
Sektor peternakan sendiri menyumbang 10-12% dari total emisi global, berkisar antara 5,5-7,5 gigaton ekuivalen CO2 (CO2e) per tahunnya. Sektor peternakan sendiri menyumbang 13-17% kecukupan kalori dan 28-33% konsumsi protein global.
Kini banyak beredar produk alternatif seperti susu kacang-kacangan sebagai alternatif susu sapi. Apabila mempertimbangkan aspek lingkungan, susu kacang memang memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan susu sapi. Tetapi dari aspek ekonomi dan nutrisi, susu kacang memiliki kadar nutrisi yang lebih rendah. Untuk bisa mencapai nutrisi yang sama seperti 1 liter susu sapi khususnya protein, konsumsi susu kacang kedelai harus 13% lebih banyak. Sehingga konsumen harus membayar 66% lebih tinggi dari harga susu sapi untuk mendapatkan kadar protein yang sama. Hal ini juga berlaku sama untuk produk alternatif daging yang terbuat dari kacang kedelai.
Lab grown Food
Salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan adalah dengan aplikasi bioteknologi seperti kultur sel dan rekayasa genetika. Salah satu hasil dari teknologi kultur sel adalah pengembangan lab grown food atau disebut juga cultured food.
Lab grown food dihasilkan melalui sel yang diambil dari hewan dengan cara yang tidak menyakiti hewan, kemudian sel-sel tersebut diperbanyak di laboratorium, yaitu di media tumbuh yang mengandung nutrisi. Perbanyakan sel-sel ini umumnya dibantu oleh mikroorganisme seperti E.coli.
Selama ini E.coli lebih dikenal sebagai bakteri jahat atau istilahnya bakteri patogen. Tetapi dalam teknologi DNA, E.coli sangat disenangi oleh para ilmuwan dikarenakan tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses di laboratorium, tingkat pertumbuhan yang cepat, dan kemampuan ekspresi protein yang tinggi, serta sudah banyak ilmu yang mempelajari jalur biosintesis protein dari E. coli.
Secara singkat, teknologi ini memungkinkan produksi pangan yang berasal dari hewan tanpa membutuhkan atau menyakiti hewan itu sendiri. Selain makanan, saat ini juga banyak dilakukan pengembangan lab grown ingredient seperti kolagen dan minyak.
Akan tetapi, artikel kali ini kita membahas lab grown food yaitu susu, daging, ikan, dan kopi.
Lab grown milk
Kandungan protein utama di hampir semua susu yang dihasilkan mamalia adalah kasein. Komposisi protein kasein dalam susu mencapai 80% dari total protein. Protein kasein sendiri merupakan sumber asam amino utama yang paling seimbang dibandingkan telur ayam dan kacang kedelai.
Seiring dengan bertambahnya populasi masyarakat yang memilih plant based milk atau gaya hidup vegetarian dan vegan, protein kasein yang merupakan sumber nutrisi ideal dari susu menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen plant based milk. Beberapa penelitian berhasil memproduksi kasein tanpa sapi, yaitu dengan melakukan rekayasa genetika pada E.coli dengan memasukan sel sapi, sehingga bakteri tersebut mampu memfermentasi gula menjadi protein kasein. Kemudian protein kasein diperbanyak di tangki fermentasi.
Hingga saat ini, sudah ada 2 perusahaan yang menjual lab grown milk, yaitu Remilk™ dari Israel dan Perfect Day® dari California. Remilk™ memiliki slogan “Real Dairy. No Cows.” dan mengklaim produknya sebagai produk susu yang bernutrisi, cruelty free, dan sustainable. Sementara Perfect Day®, selain memproduksi susu juga sudah memiliki produk whey protein pertama di dunia yang tidak berasal dari hewan.
Lab grown meat
Saat ini sudah mulai banyak restoran yang menyediakan plant-based meat. Bentuknya saja yang menyerupai daging, tapi sebenarnya dia adalah olahan kacang-kacangan atau jamur.
Plant based meat menjadi opsi yang lebih ramah lingkungan, dikarenakan untuk produksi kacang-kacangan atau jamur membutuhkan air dan lahan yang lebih sedikit dibandingkan peternakan serta mengeluarkan emisi karbon yang jauh lebih sedikit dibandingkan peternakan sapi.
Lab grown meat atau cultured meat sudah banyak diteliti dan dikembangkan dengan teknologi kultur sel dan rekayasa genetika yang dapat menghasilkan jaringan daging dan otot yang sangat mirip dengan produk daging asli.
Lab grown meat dibuat dengan memperbanyak sel induk dari sel lemak atau otot dari hewan di dalam media kultur. Media kultur tersebut mengandung nutrisi yang digunakan oleh sel induk tersebut untuk berkembang dan memperbanyak diri. Lab grown meat sendiri lebih ramah lingkungan karena tidak membutuhkan lahan.
Pada tahun 2020, Singapura menjadi negara pertama yang mendapatkan persetujuan dari regulasi untuk mengkomersialisasikan produk lab grown meat. Hal ini dimulai oleh perusahaan start up bernama Eat Just Inc. yang telah berusaha selama 2 tahun terakhir untuk mendapatkan persetujuan.
Produknya yang diberi merek Good Meat diklaim memiliki kandungan protein yang tinggi dengan komposisi asam amino yang lengkap, tanpa antibiotik, dan kandungan mikroba yang sangat rendah. Produk lab grown meat dari perusahaan ini yaitu daging dada ayam dan nugget sudah dijual di beberapa restoran bahkan di pusat jajanan.
Di Amerika Serikat, perusahaan bernama Orbillion Bio mengembangkan lab grown wagyu beef dan diharapkan dapat dipasarkan pada tahun 2025. Berbeda dengan perusahaan lainnya yang mengembangkan lab grown meat sebagai alternatif daging yang banyak beredar seperti ayam dan sapi, Orbillion Bio berfokus pada daging yang sulit dibeli oleh sebagian besar orang seperti daging wagyu, daging banteng, daging domba, dan daging rusa.
Lab grown fish
Selain daging, salah satu perusahaan di California bernama Wildtype berusaha memproduksi ikan yang lebih berkelanjutan, yaitu dengan membuat lab grown sushi-grade salmon melalui penumbuhan sel yang diekstrak dari telur salmon.
Salmon merupakan komoditas ikan dengan nilai tertinggi di dunia dan sangat disukai oleh konsumen. Walaupun dalam peternakan ikan tidak menghasilkan emisi karbon yang tinggi, tetapi penggunaan air yang sangat banyak menjadi perhatian.
Peternakan ikan juga umumnya diberikan antibiotik untuk menjaga kualitas ikan, tetapi pemberian antibiotik dapat menyebabkan resistensi antibiotik, dapat mengandung mikroplastik, dan limbah dari peternakan ikan dapat menjadi polusi bagi ekosistem perairan.
Ditelaah dari sisi ini, lab grown salmon menjadi pilihan yang lebih baik karena tidak mengandung antibiotik, logam berat, dan mikroplastik, serta tidak ada bagian ikan yang dibuang seperti tulang karena yang dikembangkan hanyalah bagian yang dapat dikonsumsi.
Lab grown salmon hanya memerlukan waktu empat sampai enam minggu untuk ditumbuhkan, dibandingkan dengan peternakan salmon yang memerlukan waktu dua sampai tiga tahun untuk dapat panen salmon dewasa.
Kandungan nutrisi dari salmon yang dikembangkan oleh Wildtype juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan sama seperti ikan salmon, termasuk omega-3 dan omega-6.
Lab grown coffee
Kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia, dan peningkatan permintaan pasar akan kopi mengancam keberlanjutan lingkungan. Perkebunan kopi memiliki dampak yang dapat merusak lingkungan pada jangka waktu lama, dikarenakan diperlukannya deforestasi dan penggunaan air dalam jumlah banyak.
Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri kopi juga berdampak pada perkebunan kopi itu sendiri. Resiko gagal panen pada perkebunan kopi juga tinggi dikarenakan perkebunan kopi sangat bergantung pada kondisi iklim. Diperkirakan setengah dari total perkebunan kopi dapat menjadi tidak produktif di tahun 2050 akibat krisis iklim. Sehingga VTT Technical Research Centre of Finland mencoba mencari cara yang lebih ramah lingkungan untuk memproduksi kopi.
Kopi VTT dikembangkan oleh kultur sel di dalam bioreaktor yang tinggi nutrisi. Proses ini tidak memerlukan pestisida dan membutuhkan air yang jauh lebih sedikit. Lab grown coffee dibuat dari bubuk kopi freeze dried untuk mengkonversi senyawa dari limbah tumbuhan menjadi senyawa yang terkandung dalam biji kopi. Hasil dari perbanyakan kultur sel ditambahkan dengan ekstrak biji kurma, akar chicory, kulit anggur, serta kafein, kemudian dipanggang, dihaluskan, dan kemudian diseduh untuk dijadikan kopi. Metode ini menghasilakan emisi karbon 93% lebih sedikit dan menggunakan air 94% lebih sedikit dibanding produksi kopi konvensional.
Hingga saat ini, peneliti yang mengembangkan lab grown coffee berpendapat bahwa kopi yang dikembangkan masih memiliki cita rasa yang mirip seperti teh dan mereka belum berani menelan kopi tersebut. VTT memprediksikan butuh 4 tahun untuk mendapatkan persetujuan regulasi untuk mengkomersialisasikan produk ini. Keuntungan lain dari lab grown coffee adalah kemampuannya untuk dapat diproduksi sepanjang waktu karena dapat diatur kondisi lingkungannya seperti suhu, cahaya, dan oksigen.
Tantangan di masa depan
Lab grown food memiliki potensi yang menjanjikan untuk menggantikan produk makanan konvensional yang dikonsumsi saat ini. Tetapi tentu ada hambatan dan tantangan untuk dapat memproduksi lab grown food dalam skala besar, juga di aspek pemasaran dan penerimaan konsumen.
Salah satu tantangan terbesar selain persetujuan regulasi adalah metode produksi skala besar serta efektivitas biaya. Lab grown food membutuhkan media pertumbuhan yang mengandung asam amino, nutrisi, dan faktor pertumbuhan seperti insulin dan transferrin untuk sel agar dapat bertumbuh dan memperbanyak diri.
Saat ini, media tersebut harganya mahal karena proses produksinya amat rumit. Insulin dan transferrin didapatkan dari hewan ternak, sehingga sulit didapatkan dalam jumlah banyak. Insulin dan transferrin juga bisa didapatkan melalui fermentasi kapang atau bakteri, tetapi metode ini membutuhkan fasilitas yang juga mahal.
Penerimaan konsumen untuk lab grown food juga sangat menentukan. Penerimaan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah paparan media sosial dan perbedaan budaya. Konsumen di Singapura lebih dapat menerima lab grown food dibandingkan konsumen di Amerika, misalnya, dikarenakan masyarakat Singapura memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mencoba sesuatu walaupun hanya melihat gambarnya. Budaya FOMO (fear of missing out) di Singapura juga menjadi faktor motivasi untuk konsumen mau mencoba lab grown food.
Terakhir, regulasi yang mengatur penjualan lab grown food juga menjadi salah satu tantangan. Hingga saat ini hanya ada satu negara yang memperbolehkan penjualan lab grown food, yaitu Singapura melalui Singapore Government Food Agency (SFA). Proses untuk regulasi pun memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Bagaimana menurut kamu, apakah lab grown food bisa jadi solusi akan krisis pangan? Apakah menurut kamu masyarakat Indonesia bisa menerimanya?
BACA JUGA: Mengenal Makanan Fungsional